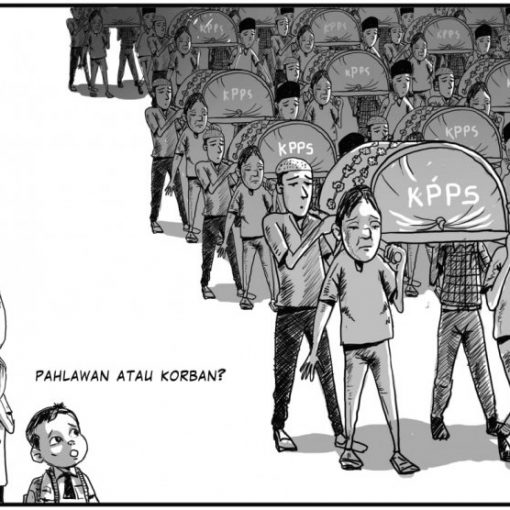Kasus kematian pria kulit hitam, George Floyd, saat ditangkap polisi kulit putih di Minneapolis, Minnesota, 25 Mei, memicu gelombang kerusuhan massa di sejumlah tempat di AS.
Floyd ditangkap karena dicurigai menggunakan uang kertas palsu. Merujuk The New York Times, demonstrasi dan kerusuhan terjadi di setidaknya 140 kota. Para wali kota pun memberlakukan jam malam di hampir 40 kota. Ini pemberlakuan jam malam terluas di AS sejak 1968 menyusul terbunuhnya Martin Luther King Jr yang kala itu, seperti kini, terjadi pada musim kampanye pilpres.
Kasus ini menambah panjang daftar konflik karena masalah rasial di AS. Sebelum kasus Floyd, dalam periode enam tahun terakhir, menurut CNN Indonesia, terjadi sekitar delapan kasus lain yang melibatkan orang kulit hitam dan polisi kulit putih di AS.
Masalah rasial, khususnya diskriminasi rasial, mungkin sama tuanya dengan sejarah umat manusia. Namun, upaya melakukan sistematisasi terhadap pembagian ras baru dimulai sekitar abad ke-19. Gagasan mengenai superioritas ras dan Darwinisme Sosial mencapai titik puncaknya dalam ideologi Nazi sekitar 1930 dan memberikan justifikasi yang kurang tepat bagi kebijakan dan berbagai perilaku dari diskriminasi, eksploitasi, perbudakan, dan pembunuhan massal. Teori-teori terkait ras yang sebelumnya menegaskan adanya hubungan antara tipe ras dan kecerdasan kemudian menjadi terlihat tidak tepat.
Dari perspektif ilmu pengetahuan telah diterima bahwa terdapat beberapa subbagian dari spesies manusia, tetapi ini juga memperjelas bahwa variasi genetis di antara individu-individu dari ras yang sama dapat menjadi sama baiknya dengan anggota dari ras-ras yang lain.
Belakangan, pengaitan ras dengan ideologi dan teori-teori yang tumbuh dari hasil studi para antropolog dan psikolog abad ke-19 telah membuat penggunaan kata ”ras” itu sendiri menjadi problematis. Istilah ”masyarakat” atau ”komunitas” lebih sering digunakan.
”Landmark”
Dalam sejarah hukum AS, setidaknya ada satu putusan Mahkamah Agung (Supreme Court) AS yang berhasil menjadi semacam landmark dalam menyelesaikan masalah rasial, yaitu ”Brown v Board of Education of Topeka” (1954). Kasus berawal pada 1951 ketika suatu sekolah umum (khusus bagi orang kulit putih) di Distrik Topeka, Kansas, menolak menerima Linda Brown, putri seorang penduduk kulit hitam setempat bernama Oliver Brown, sebagai siswa. Lokasi sekolah itu terdekat dari rumahnya.
Untuk menuju lokasi sekolah khusus kulit hitam, ia harus naik bus karena jauh. Keluarga Brown dan beberapa keluarga kulit hitam lain yang senasib kemudian mendaftarkan gugatan di Federal Court melawan Topeka Board of Education. Mereka berpendapat, kebijakan pemisahan siswa di sekolah berdasarkan warna kulit inkonstitusional. Awalnya, tiga hakim panel memberikan putusan yang bertentangan dengan gugatan Brown, yakni dengan mendasarkan pada preseden putusan MA AS tahun 1896 dalam kasus Plessy versus Fergusson.
Saat itu MA memutuskan bahwa pemisahan berdasarkan rasial bukanlah pelanggaran terhadap ketentuan Amendemen XIV Konstitusi AS terkait perlindungan yang sama (equal protection clause) jika fasilitas yang dipermasalahkan adalah sama—ini kemudian menjadi suatu doktrin separate but equal. Dengan kata lain, ketiga hakim panel berpendapat pemisahan siswa di sekolah berdasar warna kulit adalah sah dan tak bertentangan dengan Konstitusi AS.
Karena tak puas dengan putusan District Court ini, pihak Brown memberikan kuasa kepada Thurgood Marshall, pimpinan The National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), organisasi yang memperjuangkan hak-hak sipil di AS, untuk mewakili mereka dalam persidangan di MA. Marshall, 13 tahun kemudian, diangkat Presiden Lyndon B Johnson sebagai hakim kulit hitam pertama di MA AS.
Dalam menangani perkara ini, MA kemudian menggabungkan kasus-kasus itu jadi satu dengan nama ”Brown v Board of Education of Topeka”. Saat itu, MA dipimpin Chief Justice Fred M Vinson; tetapi saat perkara hendak diperdengarkan di sidang Vinson meninggal. Presiden Eisenhower menunjuk Earl Warren sebagai pengganti. Dalam putusan 17 Mei 1954, MA secara mutlak menetapkan pemisahan ras terhadap anak-anak di sekolah-sekolah publik inkonstitusional.
Namun, dalam putusannya, MA tak menyatakan bagaimana tepatnya sekolah-sekolah itu harus diintegrasikan. MA justru meminta adanya argumen-argumen lebih lanjut terkait ini. Dalam realitasnya, putusan ini seperti memberikan bahan bakar bagi gerakan hak-hak sipil di AS.
Tahun 1955, Rosa Parks, seorang perempuan kulit hitam, menolak memberikan kursinya di sebuah bus di Montgomery, Alabama, kepada seorang laki-laki kulit putih. Tindakan ini memberikan inspirasi kepada pimpinan komunitas kulit hitam setempat untuk mengorganisasikan Montgomery Bus Boycott.
Pada hari di mana Parks dinyatakan terbukti bersalah melanggar UU segregasi, gerakan boikot dilancarkan di bawah pimpinan pendeta Dr Martin Luther King Jr. Boikot berlangsung setahun lebih dan berakhir saat MA menyatakan tindakan pemisahan warna kulit di dalam suatu bus inkonstitusional. Parks jadi semacam simbol bagi kehormatan martabat dan kekuatan dalam perjuangan mengakhiri pembedaan rasial.
Belajar dari pengalaman
Martin Luther King Jr kemudian menjadi salah satu tokoh gerakan sipil terkemuka di AS. Sekitar delapan tahun kemudian, tepatnya 28 Agustus 1963, dia menyampaikan pidato yang kemudian terkenal ke seluruh dunia, ”I Have a Dream”, dalam pawai ”March on Washington for Jobs and Freedom” di hadapan lebih dari 250.000 pendukung hak-hak sipil di Lincoln Memorial di Washington DC. Dia meneriakkan tuntutan untuk dipenuhinya hak-hak sipil dan ekonomi serta diakhirinya rasisme di AS.
King mengutip Emancipation Proclamation yang mendeklarasikan pembebasan jutaan budak tahun 1863, ”One hundred years later, the Negro still is not free,” ujarnya. King mendeskripsikan mimpinya tentang kebebasan dan persamaan di wilayah yang dulunya merupakan tempat perbudakan dan kebencian.
Menurut pengamatan saya, sebagai bangsa besar dan salah satu negara terkemuka di dunia, seyogianya AS mencoba belajar dari pengalaman historis yang pernah terjadi dan berhasil diselesaikan melalui putusan-putusan monumental MA-nya.
Prof. Dr. Satya Arinanto Arinanto, S.H., M.H.
Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Artikel ini telah dimuat dalam Harian Kompas, 17 Juni 2020