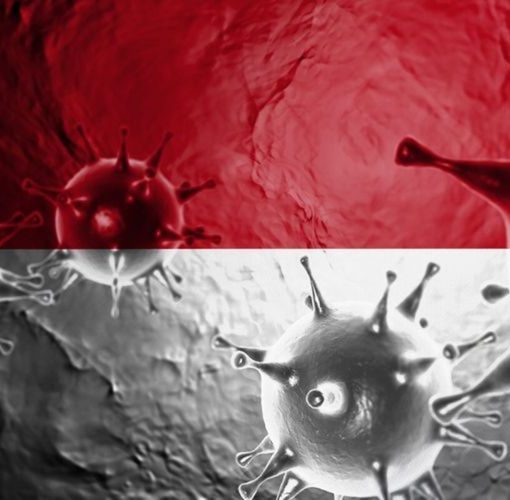Eskalasi perdebatan mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, yang secara resmi diperkenalkan sebagai RUU Ciptaker, tidak dapat dihindarkan dalam ruang publik belakangan ini meskipun perdebatan mengenai problematika dan penanganan pandemi Covid-19 pun belum mereda. Sebagian orang, terutama sarjana hukum, mempersoalkan metode omnibus yang ditempuh Pemerintah sebagai pengusul. Sementara itu tidak sedikit juga yang mempermasalahkan materi dalam RUU tersebut yang bisa dibilang sangat ‘berat’.
Konsep RUU yang diserahkan Pemerintah kepada DPR pada Februari 2020 lalu merupakan naskah setebal 1.028 halaman ditambah Naskah Akademis-nya setebal 1.981 halaman. RUU Ciptaker terdiri dari “hanya” 15 bab dan 174 pasal. Namun substansi isinya memuat sekira 1.200an ketentuan, yang banyak mengubah ketentuan dari 79 UU berbagai sektor yang saat ini berlaku. Secara harfiah, RUU ini merupakan RUU yang berat.
‘Executive Heavy’
Salah satu pokok yang membuat RUU menjadi sangat berat adalah angan-angan menguatnya wewenang Presiden sebagai pemimpin tertinggi eksekutif, terutama terkait perizinan dan legislasi. Contoh pertama adalah pengambilalihan wewenang perizinan oleh Pemerintah Pusat yang saat ini berlaku dalam beberapa UU sektoral diatur merupakan wewenang menteri ataupun pemerintah daerah.
Peliknya, RUU ini mendefinisikan Pemerintah Pusat sebagai Presiden sebagai pejabat tunggal. Padahal pasca reformasi, pembagian wewenang pemerintah telah didesain sedemikian rupa sehingga Presiden dibantu oleh para menteri dan pemerintah daerah. Apabila nantinya wewenang-wewenang eksekutif mayoritas dipegang oleh Presiden maka semua beban kerja akan menumpuk padanya. Kekhawatiran lainnya akan adanya potensi kerusakan sistem pembagian tugas dan wewenang yang selama ini telah dibangun berdasarkan UU tentang Kementerian Negara maupun UU tentang Pemerintahan Daerah, yang justru tidak ikut dalam gerbong RUU Ciptaker ini.
Kedua adalah penguatan wewenang Presiden lainnya adalah terkait legislasi. Sebagaimana telah ramai dipermasalahkan sebelumnya, Pasal 170 RUU tersebut memberikan wewenang kepada Peraturan Pemerintah untuk dapat mengubah ketentuan yang diatur dalam suatu UU. Masyarakat umum mempertanyakan bagaimana mungkin produk hukum Presiden bisa menganulir produk hukum yang dikeluarkan oleh para wakil rakyat. Membaca naskah pasal tersebut serasa membawa kita kembali ke masa lampau di mana kekuasaan eksekutif begitu besar dan tanpa penyeimbang.
Ketiga adalah wewenang Presiden melalui peraturan pemerintah untuk membentuk lembaga-lembaga negara yang dalam RUU ini berpotensi menghadirkan 9 lembaga negara, beberapa di antaranya baru. Beberapa yang lama, sebetulnya sudah diatur dalam UU yang saat ini berlaku, misalnya: dewan pengupahan (diatur dalam UU Ketenagakerjaan), lembaga sertifikasi dan lembaga jasa konstruksi (UU Konstruksi), dewan nasional dan dewan kawasan (UU KEK). Akan tetapi bedanya, RUU ini menghendaki semuanya dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ataupun Keputusan Presiden, yang sebelumnya sudah dibentuk berdasarkan peraturan setingkat menteri. Dalam implementasinya nanti hampir dapat dipastikan berimplikasi secara administrasi kelembagaan dan keuangan.
Sedangkan lembaga yang dikehendaki terbentuk baru di antaranya adalah kelembagaan yang terkait investasi pemerintah pusat. Pasal 156 RUU mengatur pembentukan Lembaga Pengelola Investasi yang ditempeli wewenang untuk mengelola investasi Pemerintah Pusat yang berasal dari penyertaan negara. Struktur utamanya terdiri dari Dewan Pengarah dan Komisioner, mirip sekali dengan unsur suatu perseroan yang terdiri dari Direksi dengan Dewan Komisaris.
Apabila dicermati, cita-cita pembentukan lembaga ini sepertinya mirip seperti suatu sovereign wealth fund, yaitu suatu lembaga negara yang mengelola investasi negara ke dalam produk-produk investasi yang tersedia di pasar seperti saham, surat utang maupun sektor ril seperti properti. Biasanya negara maju yang memiliki surplus anggaran dan rasio utang sangat rendah yang membentuk lembaga tersebut. Negara seperti Amerika Serikat dan Jepang membentuk SWF dalam rangka mengelola dana-dana yang tersedia antara lain untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.
Dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini ditambah terpaan pandemi, pertanyaan pokoknya adalah apakah anggaran negara dan perekonomian negara sudah mapan untuk keberadaan lembaga pengelola investasi tersebut. Secara umum, publik harus mempertanyakan apa urgensi lembaga-lembaga baru tersebut. Apakah lembaga yang ada tidak mampu atau tidak lagi dapat dipercaya? Atau apakah ada suatu urusan pemerintahan yang baru namun belum ada yang mengurusinya?
Implikasi Terhadap Pengadilan
Implikasi lain secara kelembagaan tentunya adalah terhadap pengadilan dalam hal terkait penegakan hukum dan pelaksanaan putusan. Dalam RUU ini setidaknya ada 21 urusan menghendaki peran dari pengadilan sebagai penyelesainya. Misalnya dalam hal gugatan wilayah pesisir, kepailitan di pengadilan niaga, pembubaran perseroan, pencabutan izin, hingga pidana terkait ketenagakerjaan. Sayangnya RUU ini tidak mengatur detil tata cara penyelesaian setiap problem hukum tersebut.
Pembuat UU biasanya tidak mau repot memikirkan cara penyelesaian di perkara atau sengketa di pengadilan. Hal ini terbukti Mahkamah Agung seringkali menerbitkan Peraturan MA yang terkait hukum acara karena suatu UU tidak mengatur detil. Beberapa contoh antara lain terkait tata cara penanganan keberatan putusan KPPU, mediasi dan penanganan gugatan perdata secara elektronik. Contoh lain di bidang pidana terkait batas minimum tindak pidana ringan, ataupun penelusuran dan penyitaan aset dalam tindak pidana pencucian uang.
Hal paling unik dalam perkembangan hukum acara adalah Peraturan MA tentang Gugatan Sederhana, yang sebetulnya secara asas dan materi menabrak hukum acara perdata ataupun UU Kekuasaan Kehakiman. Selama Peraturan MA berlaku, belum nampak aksi nyata pembuat UU untuk mengatur hukum acara gugatan sederhana dalam produk hukum selevel UU, untungnya masyarakat menerima dan memanfaatkannya.
Aspek lain yang masih luput dari pemikiran Pemerintah dan DPR adalah pelaksanaan putusan, terutama putusan perdata. Semenjak reformasi peradilan satu atap, MA terpaksa mengurus sendiri pelaksanaan putusan. Padahal pelaksanaan putusan yang berhasil ini adalah bagian dari pemenuhan hak warga dan dari perspektif bisnis juga sangat penting.
RUU ini memang sudah mengatur sedikit tentang hal itu, yaitu adanya bantuan dari kepolisian dalam hal pelaksanaan putusan. Namun itu bukanlah hal baru karena selama ini praktik di lapangan, jurusita pengadilan selalu berkoordinasi dengan kepolisian setiap akan melakukan eksekusi putusan terutama eksekusi tanah dan bangunan.
Akan tetapi permasalahannya tidak sebatas itu, karena keberhasilan pelaksanaan putusan bergantung pada banyak aspek antara lain terkait penyitaan aset, penelusuran aset, keterbukaan dan kepatuhan lembaga pemerintah terkait putusan pengadilan. Selama ini pengadilan sulit berhasil melaksanakan hal-hal tersebut karena terbentur dengan wewenang lembaga lainnya yang diatur dalam UU sektoral. Padahal jika mau meningkatkan investasi, sebagaimana cita-cita RUU ini, proses penegakan hukum (kontrak) dan pelaksanaan putusan merupakan faktor penting yang juga harus dibereskan permasalahannya.
Dalam konteks lebih luas patut direnungi bahwa MA dan aparaturnya bukanlah legislator yang juga harus memikirkan menerbitkan peraturan bagaimana suatu perkara atau masalah diselesaikan. Oleh karenanya perlu peran dan pemikiran menyeluruh dari pemerintah maupun DPR terkait masalalah-masalah di dunia peradilan.
Peran DPR
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa RUU ini secara substansial sangatlah ‘berat’. Kini bola pembahasan ada pada DPR yang harus menyadari posisinya sebagai pemegang kekuasaan pembentuk UU. DPR bukanlah rekanan apalagi sub-kontraktor Pemerintah yang harus turut targetan Pemerintah yang menginginkan selesai dalam 100 hari. DPR harus mempertimbangkan tingkat urgensi dan kebutuhan masyarakat umum dalam membahas RUU ini, terlebih dalam kondisi pandemi saat ini kebutuhan masyarakat adalah jaminan keamanan dan pelayanan kesehatan.
Dalam proses pembahasan nantinya DPR harus terlebih dahulu dapat mendefinisikan dan menata metode penyusunan omnibus bill. DPR dapat menggunakan waktu yang ada sebaiknya-baiknya, mendengarkan lebih banyak dari masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat multistakeholders karena RUU ini mengatur jangkauan dan sasaran yang sangat beragam.
Yunani Abiyoso, S.H., M.H.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI