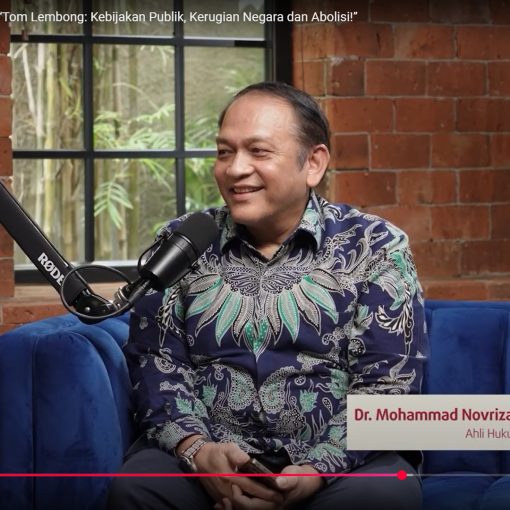Pada hari ini, 66 tahun silam, yakni 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan suatu keputusan penting untuk mengatasi krisis konstitusional yang terjadi di Indonesia pada waktu itu. Keputusan itu dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menandai berakhirnya berlakunya UUD Sementara (UUDS) 1950 dan kembalinya Indonesia ke UUD 1945.
Pada prinsipnya, keputusan ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yakni (1) Konstituante bersama-sama pemerintah gagal menyusun dan menetapkan suatu UUD yang baru sebagaimana dimandatkan Pasal 134 UUDS 1950; (2) situasi politik tak stabil karena banyaknya partai politik dan terjadinya tarik-menarik ideologi yang menyebabkan jalannya pemerintahan jadi tidak stabil. Selain itu, (3) munculnya desakan dari berbagai pihak, termasuk TNI dan rakyat, agar Indonesia kembali memberlakukan UUD 1945.
Sebagaimana kita ketahui, Pasal 134 UUDS 1950 menyatakan: ”Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini.”
Dengan demikian, Konstituante merupakan badan perwakilan rakyat yang dibentuk khusus untuk menyusun UUD baru. Tugas utamanya merumuskan UUD (konstitusi) yang lebih permanen, untuk menggantikan UUDS 1950 yang sesuai dengan namanya bersifat sementara. Pasal 134 UUDS 1950 secara tegas mengamanatkan bahwa Konstituante, bersama dengan pemerintah, harus segera menyusun UUD baru.
Kegagalan Konstituante
Meski demikian, Konstituante yang terbentuk setelah diselenggarakannya pemungutan suara kedua dari Pemilu 1955 pada 15 Desember 1955 itu ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam menyusun UUD yang baru.
Hal ini menyebabkan diterbitkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berdasarkan Keppres No 150/1959 tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945, substansinya adalah sebagai berikut: (1) menetapkan pembubaran Konstituante; (2) menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini.
Kemudian, (3) pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Beberapa implikasi dari diterbitkannya dekrit itu adalah: (1) berakhirnya sistem parlementer dan dimulainya sistem quasi-presidensial di bawah UUD 1945; (2) lahirnya demokrasi terpimpin di Indonesia; dan (3) meningkatkan kekuasaan presiden secara signifikan.
Dalam perjalanannya, meski secara hukum dianggap dilakukan di luar prosedur hukum formal, dekrit ini dianggap sebagai langkah penyelamatan negara dari kekacauan konstitusional. Pada awalnya, terbitnya dekrit menimbulkan pro-kontra terkait keabsahannya.
Bung Hatta (Wakil Presiden RI 1945-1956) dan Prawoto Mangkusasmito (Wakil Ketua Konstituante dari Partai Masyumi) berpandangan dekrit tersebut inkonstitusional dan merupakan suatu kudeta. Meskipun prosedur pemberlakuan dekrit ini dilakukan melalui hukum tata negara darurat (staatsnoodrecht), tetapi kemudian ia diterima secara politis dan mendapatkan legitimasi secara de facto maupun de jure.
Peranan Wirjono dan penyesalan Wilopo
Meskipun bukan sebagai pengambil keputusan utama, Prof Wirjono Prodjodikoro (Menteri Kehakiman 1957-1959; dan Ketua Mahkamah Agung 1966-1968) memiliki peranan penting dalam proses penyusunan dekrit.
Ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman dalam Kabinet Karya di bawah Perdana Menteri Djuanda, ia mendukung langkah diberlakukannya kembali UUD 1945 karena Konstituante cenderung gagal dalam mengesahkan konstitusi baru. Ia melihat bahwa keadaan darurat memerlukan suatu solusi luar biasa yang bisa dibenarkan dalam keadaan kekacauan politik saat itu.
Ia dianggap telah memberikan suatu interpretasi konstitusional yang membenarkan (menjustifikasi) bahwa Presiden memiliki kekuasaan untuk mengambil tindakan demi keselamatan negara. Sebagai seorang pakar hukum tata negara dan pejabat tinggi negara di bidang hukum, ia memberikan pembenaran hukum dan dorongan untuk kembali ke UUD 1945, ketika sistem parlementer dianggap gagal.
Frasa dalam naskah dekrit yang dinilai dijustifikasi oleh pemikiran Wirjono itu antara lain sebagai berikut: ”Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi”.
Kalimat inilah antara lain yang memberikan justifikasi bahwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu harus diterima sebagai satu-satunya jalan konstitusional untuk menyelamatkan kondisi Negara RI, yang kemudian disebut sebagai Hukum Tata Negara Darurat (Staatsnoodrecht). Dengan terbitnya dekrit ini, sistem parlementer pun berakhir, dan kita kembali ke sistem quasi-presidensial di bawah UUD 1945.
Di sisi lain Wilopo, yang saat itu ketua Konstituante dari unsur Partai Nasional Indonesia (PNI), dalam tiga jilid bukunya yang berjudul Tentang Dasar Negara dalam Konstituante (1958), sangat menyesalkan Konstituante dibubarkan sebelum menyelesaikan tugasnya melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Namun, di sisi lain, dia juga memahami bahwa situasi politik saat itu telah buntu. Dia menyimpulkan bahwa perdebatan di Konstituante mengenai dasar negara Indonesia—apakah Pancasila, Islam, atau ideologi lain—di samping mencerminkan keragaman masyarakat Indonesia, juga memperlihatkan kurangnya kemauan untuk mencapai kompromi nasional. Akibatnya, Konstituante gagal menjalankan tugas utama menyusun UUD baru sesuai amanat Pasal 134 UUDS 1950.
Pandangan Wilopo ini juga didukung hasil penelitian disertasi Adnan Buyung Nasution di Utrecht University, Belanda yang kemudian diterbitkan dalam buku berjudul The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante, 1956-1959 (1992).
Adnan, antara lain, menyimpulkan bahwa dekrit itu merupakan suatu kemunduran terhadap cita-cita negara konstitusional, karena memberi kekuasaan besar kepada Presiden dan mengakhiri sistem demokrasi parlementer.
Selanjutnya, Adnan menyatakan bahwa sejak terbitnya dekrit itu, pemerintahan Indonesia cenderung otoriter, dan peran institusi-institusi konstitusional seperti parlemen dan pengadilan menjadi lemah. Penegakan prinsip negara hukum (Rechtstaat) dan perlindungan HAM belum sepenuhnya terwujud, karena sering dikalahkan oleh kepentingan politik dan kekuasaan negara.
Meski demikian, aspirasi terhadap pemerintahan konstitusional tetap hidup, terutama melalui perjuangan para tokoh masyarakat sipil (civil society) dan reformasi hukum pasca-Orde Baru.
Pelajaran berharga
Bagi Wilopo, pelajaran berharga dari kegagalan Konstituante yang menyebabkan terbitnya dekrit adalah pentingnya kesepakatan nasional tentang dasar negara yang harus melandasi seluruh bangunan hukum dan politik Indonesia dalam jangka panjang.
Dengan demikian, beberapa inti dari pemikiran Wilopo yang dapat dijadikan pelajaran berharga dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia di masa depan adalah sebagai berikut. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah suatu jalan tengah. Dia menilai Pancasila merupakan titik temu antara berbagai pandangan ideologis dan mencerminkan realitas majemuk bangsa Indonesia.
Kedua, pertentangan ideologis menghambat kemajuan. Perdebatan di sidang-sidang Konstituante terlalu terfokus pada perdebatan teologis (negara Islam versus negara sekuler), sehingga mengabaikan kebutuhan praktis bangsa untuk memiliki suatu UUD baru yang stabil dan operasional, pengganti UUDS 1950.
Ketiga, kegagalan Konstituante merupakan kegagalan elite politik. Wilopo menilai para anggota Konstituante gagal menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan partai dan kelompok masing-masing. Keempat, pentingnya sikap kenegarawanan dan kompromi. Untuk membangun negara hukum yang demokratis diperlukan sikap kenegarawanan, bukan fanatisme ideologis. UUD seharusnya jadi alat pemersatu, bukan alat perpecahan.
Pandangan Wilopo dan Adnan antara lain diperkaya Herbert Feith dalam buku klasiknya, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (1962), yang menggambarkan kemunduran demokrasi konstitusional di Indonesia di masa awal kemerdekaan (1950-1959), dan menjelaskan mengapa sistem demokrasi parlementer gagal bertahan.
Feith menyimpulkan, demokrasi konstitusional di Indonesia tak berhasil berkembang secara stabil karena berbagai faktor politik, sosial dan institusional. Dengan demikian, Feith—Indonesianis dan profesor Ilmu Politik yang mengajar di Monash University—lalu menyimpulkan beberapa hal penting berikut.
Pertama, masa demokrasi parlementer ditandai oleh instabilitas politik, seringnya kabinet jatuh-bangun, dan ketidakmampuan elite politik membangun konsensus nasional. Partai politik lebih mengutamakan kepentingan sempit (ideologis) daripada kepentingan nasional.
Kedua, terjadi persaingan tajam antara kelompok nasionalis, Islamis, Komunis, dan Sosialis. Polarisasi ideologis ini melemahkan pemerintahan dan menyebabkan kebuntuan, terutama dalam sidang Konstituante yang gagal menetapkan UUD yang baru.
Ketiga, melemahnya lembaga demokratis, yaitu, lembaga seperti parlemen dan kabinet tidak berfungsi efektif. Sementara itu, militer dan Presiden malah mulai memperbesar pengaruhnya di luar mekanisme konstitusional.
Keempat, kembalinya pola kepemimpinan pribadi. Akibat kekecewaan terhadap sistem parlementer, Presiden Sukarno kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden. Hal ini membuka jalan bagi diterapkannya prinsip ”Demokrasi Terpimpin”. Dalam sistem demokrasi ini, terjadi perubahan dari Rule of Law ke Rule of Man, ketika kekuasaan menjadi terpusat pada Presiden, dan bukan pada hukum atau lembaga.
Feith melihat ini sebagai titik akhir dari harapan terhadap sistem politik demokratis yang berdasarkan hukum. Pandangan senada Wilopo, Adnan, dan Feith juga ditemukan di buku Daniel S Lev, profesor di University of Washington, The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959.
Dalam buku Lev ini dikemukakan bahwa terjadinya berbagai kudeta di daerah-daerah, seperti PRRI-Permesta, telah menggoyahkan stabilitas nasional. Ini mengakibatkan Sukarno menetapkan keadaan darurat dan memperkuat posisi militer. Terjadilah penyusunan kembali kekuasaan: militer masuk politik, dan partai politik mulai dibatasi.