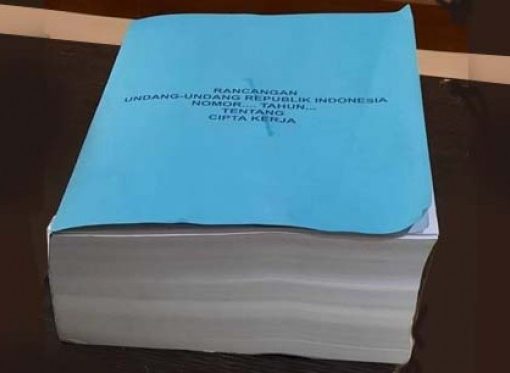“Saat ekonomi dibuka kembali, aktivitas-aktivitas akan pulih, namun jangan berharap akan kembalinya dengan cepat suatu dunia yang riang dengan gerakan yang lebih baik dan perdagangan bebas.”
Pada 20 Januari 2021 yang akan datang, Joe Biden akan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) ke-46, menggantikan Donald J Trump. Pergantian kepemimpinan di AS ini menimbulkan pertanyaan: bagaimanakah wajah globalisasi pasca-Trump?
Dalam pandangan Peterson Institute for International Economics (PIIE), suatu lembaga riset yang bersifat nonprofit dan nonpartisan yang berkantor di Washington, DC, globalisasi merupakan suatu kata yang antara lain dipergunakan untuk menggambarkan interdependensi dari ekonomi, budaya, dan kependudukan dunia; yang disebabkan oleh perdagangan dan pelayanan, teknologi, dan aliran investasi, masyarakat, dan informasi yang melewati batas-batas negara.
Berbagai negara telah membangun kemitraan ekonomi untuk memfasilitasi gerakan-gerakan tersebut dalam beberapa abad. Istilah “globalisasi” ini mencapai popularitasnya pada pasca Perang Dingin pada awal tahun 1990-an, ketika pengaturan-pengaturan kerjasama ini telah berhasil membentuk kehidupan sehari-hari yang modern dewasa ini.
Sebagaimana diketahui, Donald J. Trump yang menjadi Presiden AS sejak 20 Januari 2017, telah melemparkan semacam granat tangan ke dalam ekonomi global – diantaranya terkait pengaturan mengenai pergerakan barang-barang, berbagai pelayanan, dan modal melewati perbatasan negara-negara dan berupaya untuk menjamin stabilitas.
AS merupakan negara yang berperan penting dalam pembentukan sistem-sistem tersebut pada masa pasca Perang Dunia II. Sebagian karena sistem-sistem tersebut, pada periode paruh kedua dari abad ke-20 telah ditandai berbeda dari periode paruh pertama, yang antara lain diwarnai oleh peristiwa terjadinya 2 Perang Dunia – Perang Dunia Pertama dan Kedua – dan juga kejatuhan besar di bidang keuangan dan industri pada tahun 1929 dan sesudahnya, atau yang dikenal sebagai Great Depression.
Great Depression
Untuk merespons kesulitan-kesulitan dalam masa Great Depression tersebut, Presiden AS ke-32, Franklin Delano Roosevelt (FDR), kemudian menerapkan suatu agenda domestik yang kemudian dikenal sebagai politik New Deal, atau selengkapnya disebut The New Deal of Roosevelt.
Sebagai seorang tokoh pimpinan dalam partai politiknya, Partai Demokrat, dia kemudian membentuk New Deal Coalition, yang diantaranya mendefinisikan liberalisme modern di AS dalam periode pertengahan ketiga dari abad ke-20. Dia merupakan satu-satunya Presiden AS yang menjabat hingga 4 periode; dimana periode ketiga dan keempat dari pemerintahannya didominasi oleh peristiwa Perang Dunia Kedua, yang kemudian berakhir tidak lama setelah dia meninggal dunia di kantornya.
Setelah Presiden FDR meninggal dunia, wakil-wakil dari berbagai negara di dunia kemudian berkumpul di San Fransisco pada 26 Juni 1945. Mereka kemudian bekerja keras merancang pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (United Nations), melalui pembentukan Piagam PBB (United Nations Charter), untuk menggantikan lembaga sebelumnya yaitu Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations).
Dalam Piagam PBB tersebut, kata “human rights” sampai disebut hingga 7 kali. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya faktor penegakan hak asasi manusia (HAM) sebagai latar belakang pembentukan PBB.
Disamping itu, pengalaman Presiden FDR yang menjabat hingga 4 periode tersebut juga telah membawa implikasi pembentukan Amandemen Pasal XXII Konstitusi AS. Dengan ketentuan tersebut, seorang Presiden AS hanya boleh menjabat maksimal selama 2 periode masa jabatan saja.
Semenjak Presiden Pertama AS yang dijabat oleh George Washington hingga Presiden FDR, sebenarnya dalam Konstitusi AS tidak ada suatu pengaturan yang eksplisit mengenai pembatasan berapa periode seorang Presiden AS boleh menjabat. Artinya, sebelum itu pembatasan dilakukan konvensi ketatanegaraan.
Antiglobalisasi pada Era Trump
Dalam bukunya mengenai Globalization and Its Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Era of Trump, Joseph Eugene Stiglitz, seorang ekonom AS, analis kebijakan publik, yang juga merupakan seorang Guru Besar di Columbia University, New York, berpendapat bahwa walau masih meninggalkan sisa-sisa asap, keadaan dunia pasca Trump akan sangat berbeda dengan pada masa sebelumnya.
Dalam pandangan peraih Hadiah Nobel dalam Bidang Ekonomi pada tahun 2001 tersebut, sementara pada masa tiga-perempat abad upaya-upaya lebih difokuskan pada pembentukan suatu dunia yang lebih terintegrasi secara global, yang melibatkan suatu rangkaian pasokan global yang telah sangat banyak menurunkan biaya barang-barang; namun kehadiran Trump kemudian mengingatkan setiap orang bahwa masalah perbatasan negara merupakan suatu masalah serius.
Pada awalnya, berbagai negara – terutama di negara-negara berkembang – menunjukkan respons yang kurang bahagia terhadap globalisasi. Menurut Stiglitz, hal ini terutama terjadi di negara-negara yang jumlah penduduknya mencapai sekitar 85 persen dari penduduk dunia; namun dengan hanya sekitar 39 persen daripada tingkat penghasilan dari penduduk seluruh dunia.
Ketidakbahagiaan ini paling banyak terjadi di Sub-Sahara Afrika, yang seringkali disebut sebagai wilayah yang dilupakan, dengan jumlah penduduk yang diperkirakan akan mencapai 2,1 milyar pada 2050.
Dewasa ini, para penentang di pasar-pasar yang baru muncul dan negara-negara berkembang disatukan oleh mereka yang berada di kelas menengah dan kelas yang lebih rendah akan kemajuan dari negara-negara industri. Presiden Trump mengambil keuntungan dari ketidakpuasan ini, dan kemudian mengkristalkan serta menggembar-gemborkannya.
Ia secara eksplisit kemudian menyalahkan bahaya yang dihadapi para pekerja di wilayah-wilayah yang mengalami penyimpangan industri – America’s Rust Belt – terhadap globalisasi – terhadap suatu penandatanganan “perjanjian perdagangan yang terburuk”. America’s Rust Belt merupakan wilayah Northeastern dan Midwestern di AS yang telah mengalami penyimpangan industri yang dimulai pada sekitar tahun 1980-an.
Terhadap upaya Trump tersebut, muncul suatu upaya yang luar biasa. AS dan negara-negara maju kemudian merumuskan aturan-aturan tentang globalisasi, dan mereka juga menggerakkan organisasi-organisasi internasional yang mengatur mengenai hal tersebut.
Keluhan-keluhan yang banyak muncul di negara-negara berkembang adalah bahwa negara-negara majulah yang telah menetapkan aturan-aturan yang terkait globalisasi tersebut dan mereka juga yang mendominasi jalannya organisasi-organisasi internasional terkait tersebut; dan hal ini tidak menguntungkan bagi negara-negara berkembang.
Berdasarkan hal tersebut, Presiden Trump mengklaim – dengan mendapatkan dukungan dari banyak pemilih di AS – bahwa perjanjian-perjanjian perdagangan dan lembaga-lembaga lain yang dibentuknya bersikap tidak adil terhadap AS.
Berakhirnya Globalisasi?
Ketika pandemi Covid-19 baru berlangsung beberapa bulan, majalah terkemuka The Economist edisi 16 Mei 2020 menampilkan cover laporan utama (laput) mengenai “Goodbye globalization: The dangerous lure of self-sufficiency”. Pada intinya laput ini mengkhawatirkan timbulnya kecenderungan timbulnya era yang lebih cenderung nasionalistis dan swasembada. Hal ini tidak mengarah kepada kondisi yang lebih kaya – atau lebih aman.
Menurut observasi majalah ini, bahkan sebelum terjadinya pandemi Covid-19, globalisasi sudah berada dalam kondisi yang bermasalah. Hal ini antara lain dilatarbelakangi oleh kondisi sistem perdagangan terbuka yang telah mendominasi ekonomi dunia selama beberapa dekade telah dirusak oleh kejatuhan finansial dan Perang Dagang AS-Cina.
Kemudian kondisi lockdown yang hingga saat ini belum jelas akan berlangsung sampai kapan telah menutup perbatasan berbagai negara dan menjatuhkan perdagangan. Tercatat misalnya bahwa jumlah penumpang pesawat di Bandara Heathrow Inggris telah mengalami penurunan hingga 97% year-on year; ekspor mobil Mexico mengalami kejatuhan sekitar 90% pada bulan April 2020 yang lalu; dan 21% dari rencana pengapalan kontainer transpasifik pada bulan Mei 2020.
Dunia sebenarnya memiliki beberapa masa integrasi, namun sistem perdagangan yang muncul pada tahun 1990-an berjalan lebih jauh daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Cina menjadi semacam pabrik dunia dan perbatasan-perbatasan dibuka bagi masyarakat, perusahaan, modal, dan informasi.
Namun setelah kasus kejatuhan Lehman Brothers pada 2008, berbagai bank dan perusahaan-perusahaan multinasional menarik kembali dananya. Perdagangan dan investasi asing mengalami stagnasi relative terhadap GDP, suatu proses yang disebut The Economist sebagai slowbalisation.
Kemudian datanglah Presiden Trump dengan perang dagangnya, yang menimbulkan campuran kekhawatiran terhadap pekerjaan kerah-biru dan kapitalisme autokratik Cina dengan suatu agenda yang lebih luas dengan agenda yang lebih luas terkait nasionalisme yang sempit dan penghinaan terhadap para aliansi.
Biaya tarif yang dikenakan AS terhadap impor telah kembali pada level tertingginya sejak 1993; dan baik AS maupun Cina telah mulai memisahkan industri-industri teknologinya.
Efek dari berbagai hal tersebut antara lain bahwa negara-negara yang lebih miskin akan semakin mengalami kesulitan untuk bertahan; dan di negara-negara maju, biaya hidup akan semakin tinggi. Dunia yang retak ini akan membuat penyelesaian masalah semakin berat, termasuk untuk memulihkan ekonomi. Pada kondisi inilah muncul pertanyaan, sudah saatnyakah kita melambaikan tangan perpisahan kepada masa keemasan era globalisasi?
Kecenderungan Pasca Trump
Kelompok populis baik yang berada di pasar-pasar yang baru muncul dan negara-negara maju memberikan suaranya terhadap ketidakpuasan para warga negaranya terhadap globalisasi; namun hanya beberapa tahun sebelumnya, para politisi yang telah memiliki kedudukan yang kuat telah menjanjikan bahwa globalisasi akan membuat setiap orang menjadi lebih baik.
Sebagaimana dinyatakan oleh Stiglitz di muka, walau masih meninggalkan sisa-sisa asap, keadaan dunia pasca Trump akan sangat berbeda dengan pada masa sebelumnya.
Saat ekonomi dibuka kembali, aktivitas-aktivitas akan pulih, namun jangan berharap akan kembalinya dengan cepat suatu dunia yang riang dengan gerakan yang lebih baik dan perdagangan bebas. Pandemi Covid-19 akan mempolitisasi perjalanan dan migrasi dan berkubu pada suatu bias yang mengarah kepada suatu kemandirian.
Pandangan yang berwawasan ke dalam semacam ini akan memperlemah pemulihan, dan membuat ekonomi rentan dan menyebarkan ketidakstabilan geopolitik.
Dalam tempo sekitar 2,5 abad ini, hasil-hasil penelitian dalam bidang ekonomi yang dimulai dari Adam Smith pada akhir abad ke-18 dan David Ricardo pada awal abad ke-19 – menyimpulkan bahwa globalisasi akan menguntungkan bagi semua negara.
Jika kesimpulan yang mereka nyatakan benar, bagaimana kita menjelaskan mengapa banyak penduduk baik di negara-negara miskin maupun berkembang memperlihatkan sikap permusuhan terhadapnya? Mungkinkah bahwa bukan hanya para politisi, namun para ekonom telah melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan globalisasi?
Ketidakpuasan-ketidakpuasan baru terlihat muncul dengan lebih kuat di AS dalam era kepresidenan Trump, sebagian karena AS telah melakukan hal-hal yang lebih besar – termasuk masalah ketidakadilan – daripada negara-negara lainnya di dunia.
Adanya berbagai kesenjangan antara hasil-hasil penelitian Adam Smith dan David Ricardo dengan realita pencapaian tujuan globalisasi pada saat ini membuat kita belum bisa memastikan bagaimana globalisasi akan tetap berperan pada era pasca Trump. Semoga kita masih bisa selalu mendambakan terciptanya the new world order; dan bukannya the new world disorder.
Satya Arinanto, Guru Besar Fakultas Hukum UI
Artikel ini dimuat dalam Harian Kompas edisi Rabu, 6 Januari 2021