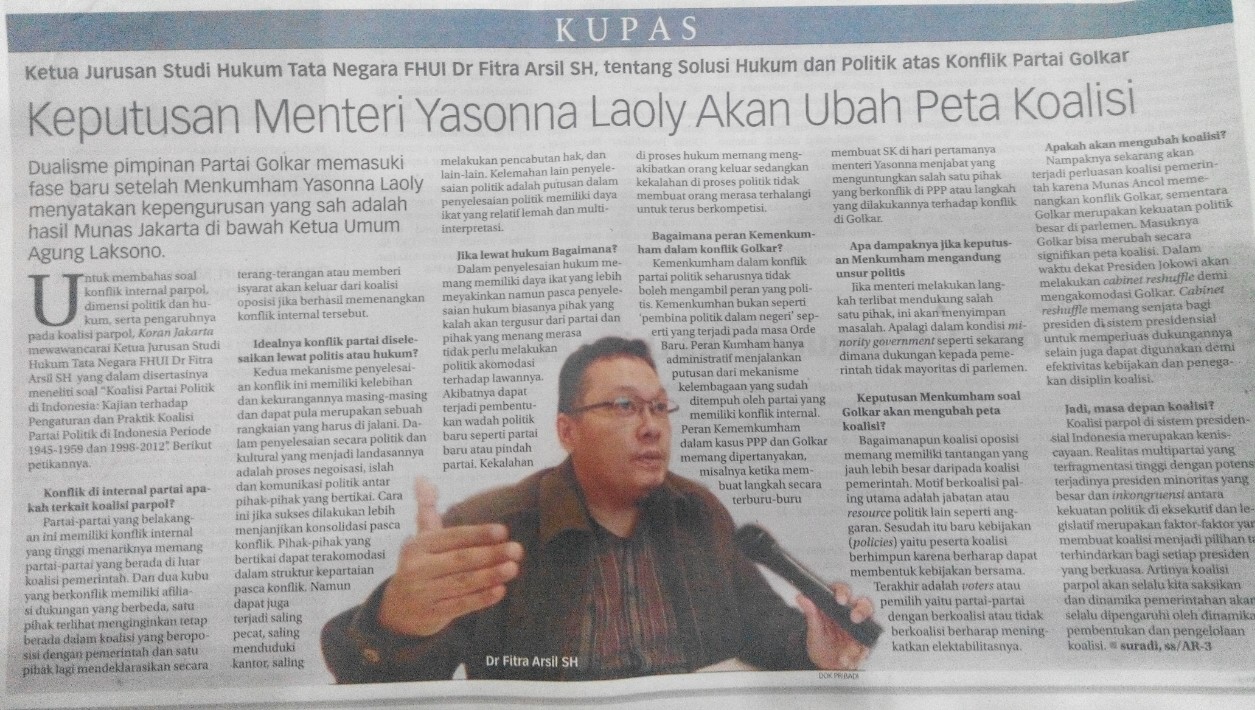Pembentukan lembaga pusat akan kontraproduktif jika masih bersifat sentralistik yang dianggap tidak mengakomodasi kebutuhan masyarakat Papua.
Pembentukan Komite Eksekutif Papua oleh Presiden memiliki pekerjaan rumah yang besar. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPPOKP) diberi amanat oleh Presiden untuk melakukan percepatan Papua. Padahal, belum genap tiga tahun lalu, Perpres No 121/2022 menandai pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Papua (BP3OP) oleh Presiden. Hal ini berarti, badan dan komite yang berasal dari pusat memiliki tugas dan fungsi yang hampir serupa.
Sebagai daerah Otonomi Khusus, Papua memiliki kewenangan khusus yang diakui dan diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Amanat UU tersebut menandakan peran masyarakat adat dan pemerintah daerah sangat penting bagi pengurusan wilayah mereka.
Namun, dengan keberadaan lembaga perwakilan pusat ini, bukan tidak mungkin dapat menjadi dasar kebijakan yang bersifat sentralistik. Salah satunya seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti di Marauke yang saat ini mengancam sosioekologis, hutan, dan budaya di Papua. Sebab, fokus utama dari badan ini terkait dengan pembangunan dan bukan memastikan otonomi khusus berjalan sebagaimana aspirasi masyarakat setempat.
Keberadaan lembaga perwakilan pusat pernah menimbulkan persoalan tersendiri, seperti yang terjadi di wilayah Batam. Konflik antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam akhirnya berakhir pada tahun 2018, ketika dualisme Batam diselesaikan oleh Presiden. Keputusan akhirnya adalah menunjuk wali kota Batam bertindak sebagai ex-officio kepala BP Batam yang telah dibentuk sejak 1971.
Otonomi Khusus Papua sendiri memiliki setidaknya empat tujuan. Pertama adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat; mewujudkan keadilan, penegakan hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi; pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua (OAP); serta penerapan tata kelola pemerintahan.
Namun, kebijakan pemerintah pusat ke Papua belum berpihak untuk memastikan otonomi khusus Papua. Penambangan nikel di Raja Ampat dan Food Estate Marauke menjadi bukti bahwa Otonomi Khusus di Papua tak dilaksanakan berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Sejak pertama kali otonomi khusus diberikan pada 2001 dan dua kali perubahan pada tahun 2021, tidak ada perubahan berarti dari arah kebijakan pusat ke Papua.
Tidak meredanya konflik
Pendekatan keamanan, militer, dan pembangunan sentralistik masih menjadi solusi terdepan dalam menangani konflik dibanding dengan pendekatan dialogis dan kesepakatan bersama. Namun, ekskalasi konflik dan teror masih terjadi bahkan pada Oktober tahun ini. Mulai dari penyelundupan senjata, penyerang KKB oleh warga, hingga kematian anggota TNI/Polri turut membuat konflik Papua belum menemukan jalan terang.
Laporan Komisi Hak Asasi Manusia yang diterbitkan pada 10 Desember 2024 mencatat, terjadi 95 kasus kekerasan di Papua dari 1 Januari-9 Desember 2024. Kasus ini menyebabkan 114 korban dengan rincian tewasnya 71 orang yang 40 di antaranya adalah warga sipil. Korban meninggal lainnya adalah 15 aparat keamanan, 15 orang sipil bersenjata, dan satu warga asing.
pologi konflik Papua berbeda dengan di Aceh. Jika GAM memiliki struktur dan komando yang relatif terorganisir, teror bersenjata di Papua dilakukan oleh faksi–faksi, kurang lebih 20 kelompok, yang tersebar di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya dengan jumlah puluhan hingga ratusan orang setiap kelompoknya. Data yang dimiliki pemerintah tersebut direspons dengan membentuk 36 Komando Daerah Pertahanan (Kodap) yang tersebar di seluruh tanah Papua.
Hendaknya pemerintah menawarkan pola penyelesaian secara horizontal dengan memberikan ruang bagi masyarakat, seperti tokoh agama, masyarakat, bahkan kelompok bersenjata untuk mencapai tujuan sebagaimana yang terdapat pada UU Otsus Papua. Hal ini tidak mustahil, mengingat pengalaman pemerintah atas penyelesaian konflik di Aceh yang formulanya merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan perwakilan tokoh Aceh, termasuk GAM.
Johan Galtung dalam peace and conflict theories mengatakan, pencegahan dan resolusi konflik satu level berada pada kendali negara. Solusi konflik sendiri adalah hasil dari kesepakatan atau perjanjian melalui hasil negosiasi dan diratifikasi oleh kedua belah pihak. Jika terlalu elisitis, pihak dalam kesepakatan tersebut dapat tidak mengakui resolusi konflik. Nantinya, akan muncul aktor lain yang menggangap dirinya tidak lagi terikat dengan resolusi konflik yang ditawarkan.
Dengan kondisi Papua saat ini, penting untuk melakukan pendekatan yang memastikan aspirasi masyarakat Papua. Pembentukan lembaga pusat akan kontraproduktif jika masih bersifat sentralistik yang dianggap tidak mengakomodasi kebutuhan masyarakat Papua. Sebagaimana pengalaman konflik di Aceh dan Yogyakarta, pemerintah pusat seharusnya berfokus untuk memberikan dan memastikan hak warga Papua dalam menjalankan hak dasar, hak adat, dan hak menjalakan pemerintahan berdasarkan kekhususan Papua dalam kerangka NKRI.
Rico Novianto, Peneliti Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI