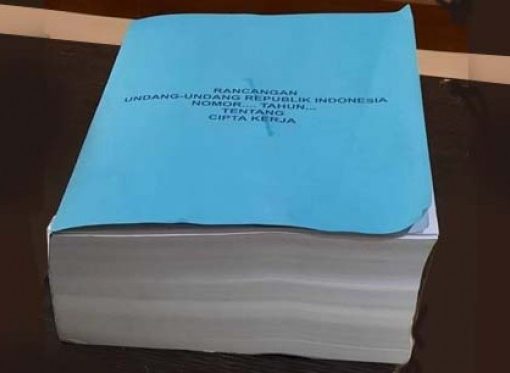Publik belum lama ini dibuat geger oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 731 Tahun 2025. Aturan itu menetapkan bahwa 16 jenis dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden, termasuk ijazah yang dilegalisasi, dianggap sebagai informasi publik yang dikecualikan.
Akses hanya bisa diberikan jika calon memberi izin tertulis atau jika pengungkapan diperlukan karena jabatan publik. Padahal, dokumen semacam itu adalah bagian penting dari proses pencalonan pilpres untuk memastikan kesahihan calon sebagai kontestan yang memenuhi syarat.
Selain itu, masyarakat berhak tahu riwayat pendidikan, profil, dan kelayakan dari calon pemimpin yang akan dipilihnya. Maka, keterbukaan bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi syarat utama agar kepercayaan publik tetap terjaga atas jalannya proses pemilu.
Tak mengherankan, keputusan KPU tersebut langsung menuai kritik keras. Pegiat pemilu, akademisi, aktivis masyarakat sipil, hingga anggota DPR mempertanyakan sikap KPU yang dianggap menabrak prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Transparansi yang seharusnya menjadi napas pemilu justru sengaja dibonsai.
Sandera politik
Gelombang kritik yang sangat deras akhirnya membuat KPU mencabut aturan tersebut meski belum genap satu bulan keberlakuannya. Sekilas, pencabutan itu bisa dibaca sebagai bentuk respons cepat terhadap aspirasi publik.
Di sisi lain, peristiwa ini membuka mata kita pada persoalan yang lebih serius. KPU mengambil keputusan tanpa dasar yang kuat. Lalu, ketika disorot publik, lantas buru-buru membatalkannya. Proses seperti itu menunjukkan lemahnya kepemimpinan kelembagaan dan rapuhnya mekanisme pengambilan keputusan.
Hal itulah yang membuat banyak pihak menilai sudah waktunya penyelenggara pemilu direset. Reset yang dimaksud bukan sekadar mengganti orang, melainkan perombakan menyeluruh atas tata kelola, budaya kerja, dan desain kelembagaan.
Sejak pemilu serentak 2019, tanda-tanda kelelahan kelembagaan sudah terasa. Kompleksitas pemilu yang begitu besar, ditambah dengan keterbatasan sumber daya, membuat penyelenggara sering bekerja dalam tekanan ekstrem.
Tetapi, masalah utamanya bukan hanya pada aspek teknis. Mekanisme perekrutan komisioner yang sarat kompromi politik, pengawasan yang inkonsisten, serta kultur organisasi yang tertutup membuat penyelenggara kehilangan kredibilitasnya. Alih-alih tampil sebagai penegak demokrasi, mereka terlihat lebih seperti operator teknis yang mudah tersandera kepentingan politik.
Karena itu, reset penyelenggara pemilu harus diarahkan pada beberapa hal penting. Pertama, pembenahan mekanisme perekrutan. Selama ini, proses seleksi di DPR lebih banyak membuka ruang patronase ketimbang meritokrasi.
Sudah saatnya kita berpikir tentang model yang lebih independen. Misalnya saja, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu mengusulkan penghapusan proses uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR dari rangkaian seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu tingkat nasional.
Kedua, perbaikan desain kelembagaan. KPU, Bawaslu, dan DKPP kerap bekerja dalam tumpang tindih kewenangan. Koordinasi cenderung lemah, hasilnya pun sering membingungkan peserta pemilu maupun pemilih. Reset kelembagaan harus menata ulang relasi antarlembaga agar saling mengawasi dan saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Apalagi sampai berkompetisi satu sama lain.
Ketiga, memperkuat komitmen transparansi. Kasus Keputusan 731/2025 adalah pengingat yang kuat untuk serius berbenah. Keterbukaan informasi bukan ancaman, melainkan syarat mutlak demokrasi. Semua data, dokumen, dan keputusan publik harus bisa diakses luas, kecuali yang memang secara tegas dirahasiakan oleh undang-undang.
Khususnya mengingat prinsip konstitusional penyelenggaraan pemilu antara lain adalah jujur dan adil. Sehingga, transparansi menjadi jalan yang tepat untuk tetap menjaga ataupun memulihkan kepercayaan publik.
Masa jabatan
Selain itu, reset kelembagaan juga harus memperhatikan aspek penataan akhir masa jabatan komisioner penyelenggara pemilu. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.120/PUU-XX/2022 telah menegaskan pentingnya kepastian hukum dan kontinuitas kepemimpinan di tubuh penyelenggara pemilu. Masa jabatan yang berakhir berserakan di tengah berlangsungnya tahapan pemilu, tanpa aturan transisi yang jelas bisa membuka ruang bagi terjadinya intervensi politik.
MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam hal pembentuk undang-undang melakukan penyesuaian UU No 7/2017, maka perekrutan penyelenggara pemilu perlu diatur agar selaras dengan prinsip keserentakan.
Pertama, proses perekrutan harus selesai sebelum tahapan pemilu dimulai. Kedua, desain perekrutan harus menghasilkan penyelenggara yang berkompeten, berintegritas, dan independen sesuai asas dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945. Ketiga, penyelenggara wajib dibekali pelatihan, workshop, atau bimbingan teknis agar mampu melaksanakan tugas dalam pemilu serentak secara efektif.
Atas dasar itu, penataan akhir masa jabatan penyelenggara pemilu harus dilakukan, agar semua anggota KPU dan Bawaslu di semua tingkatan sudah selesai direkrut sebelum dimulainya tahapan Pemilu Serentak Nasional 2029.
Tahapan Pemilu 2029 diperkirakan akan dimulai menjelang akhir tahun 2027. Konsekuensinya, harus ada akhir masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dipangkas atau dipercepat berakhirnya.
Ini bertujuan agar sebelum tahapan Pemilu Serentak 2029 dimulai, sudah terbentuk penyelenggara pemilu di semua tingkatan, yang bertugas untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak Nasional 2029 dan Pemilu Serentak Daerah pada dua atau dua setengah tahun setelahnya.
Penataan akhir masa jabatan harus menjadi bagian dari agenda reset kelembagaan, berdampingan dengan reformasi perekrutan, desain institusional, dan transparansi. Momentum untuk melakukan reset sebenarnya terbuka lebar. Apalagi waktu menuju pemilu daerah 2029 dan pemilu nasional berikutnya masih cukup panjang. Akan tetapi, waktu itu akan terbuang sia-sia jika elite politik memilih jalan pintas hanya menambal sulam kelemahan penyelenggara, lalu kembali mengulang krisis setiap kali pemilu digelar.
Kita tidak boleh membiarkan demokrasi terus diguncang oleh krisis kepercayaan. KPU dan lembaga sejenis tidak boleh terus dibiarkan menjadi sumber masalah. Melainkan harus menjadi fondasi kepercayaan atas pemilu yang kredibel.
Kasus ”dokumen rahasia capres-cawapres” memang sudah dibatalkan, tetapi itu baru langkah kecil. Jalan panjang perbaikan menanti. Mereset penyelenggara pemilu bukanlah pilihan opsional. Itu merupakan kebutuhan mendesak agar jantung demokrasi kita tetap berdetak sehat. Bila pemilu adalah jantung demokrasi, penyelenggara adalah denyut nadinya. Tanpa denyut yang kuat, demokrasi akan kehilangan nyawanya.
Kini, pilihan ada di tangan kita. Berani melakukan reset penyelenggara pemilu untuk menyegarkan demokrasi. Atau membiarkan kelembagaan yang rapuh dengan orang-orang bermasalah di dalamnya terus menggerogoti integritas bangsa.
Titi Anggraini, Pengajar Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Sumber: